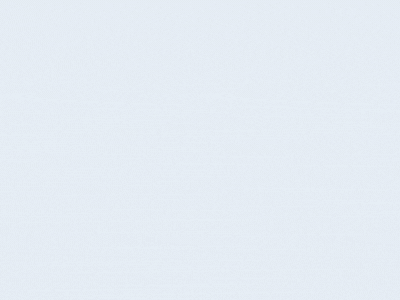Oleh: Mercy Bientri Yunindanova, S.P., M.Si., Ph.D. (Dosen Fakultas Pertanian UNS Surakarta)
FENOMENA mahasiswa Gen Z di kampus hari ini menimbulkan banyak refleksi tentang arah dan masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, pada tahun 2025 berusia 13 hingga 28 tahun. Hal ini artinya sebagian besar dari mereka kini sedang berada di masa kuliah, awal karier, atau tahap eksplorasi kehidupan profesional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (A’yun, 2025), populasi Gen Z mencapai sekitar 27,94 % dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 74,93 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada di bangku kuliah dan menjadi bagian dari 9.967.489 mahasiswa aktif di Indonesia (PDDikti, 2025).
Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti, 2025) menunjukkan bahwa dari total sekitar 9,97 juta mahasiswa, terdapat 8,28 juta mahasiswa berada di jenjang S1, sekitar 0,38 juta di jenjang S2, dan hanya sekitar 67 ribu di jenjang S3. Proporsi ini menunjukkan bahwa lebih dari 83% mahasiswa Indonesia berada pada tingkat sarjana, sedangkan mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) hanya mencakup sekitar 17% dari total populasi akademik di Indonesia.
Angka-angka ini menegaskan bahwa Gen Z adalah kekuatan demografis yang besar. Mereka akan menjadi tulang punggung produktivitas nasional di dua dekade mendatang. Namun di balik potensi tersebut, muncul fenomena yang memprihatinkan: generasi dengan tampilan gemerlap tetapi kerap kosong secara substansi intelektual.
Di banyak kampus, mahasiswa Gen Z tampil dengan penampilan nyaris sempurna, make-up lengkap, alis rapi, gaya busana trendi, dan tas modis, seolah hendak ke pusat perbelanjaan, bukan ke ruang kuliah. Hal ini tentu bukan masalah selama diimbangi dengan kedalaman berpikir, namun kenyataannya perhatian terhadap penampilan sering kali lebih menonjol daripada kesiapan akademik. Tas mereka tampak elegan, tetapi isinya lebih banyak make-up, ponsel, dan dompet dibanding buku atau alat tulis. Ini mencerminkan hilangnya prioritas belajar: kampus menjadi ruang eksistensi sosial, bukan lagi arena pengasahan intelektual.
Lebih jauh, banyak dosen mengamati melemahnya kapasitas akademik dan kepemimpinan di kalangan mahasiswa senior. Mereka yang seharusnya menjadi teladan justru kerap tidak menunjukkan kedalaman intelektual maupun kedisiplinan akademik. Akibatnya, adik kelas kehilangan figur panutan yang bisa mereka tiru dalam etika belajar, kerja keras, dan tanggung jawab ilmiah. Budaya akademik yang semestinya menumbuhkan rasa ingin tahu dan refleksi ilmiah bergeser menjadi budaya seremonial: sibuk dalam kegiatan permukaan, tetapi miskin substansi. Mahasiswa sulit mengatur waktu, tidak efisien dalam bekerja, dan mudah terdistraksi oleh media sosial. Mereka hadir di kampus secara fisik, tetapi pikiran sering kali mengembara ke ruang digital.
Fenomena ini tampak nyata dalam kualitas presentasi dan tugas akademik. Banyak tugas dibuat layaknya promosi produk, desain penuh efek, animasi mencolok, dan tata letak menarik, tetapi ketika dikaji, argumen ilmiahnya dangkal, datanya minim, dan analisisnya lemah. Gaya menjadi lebih penting daripada isi. Dalam forum ujian, muncul pula penggunaan bahasa gaul seperti “OKE” atau “SIAP, Pak,” yang menurunkan wibawa akademik. Bahasa ilmiah yang seharusnya menunjukkan logika, ketelitian, dan ketajaman berpikir justru digantikan oleh bahasa ringan tanpa substansi.
Jika pola ini dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan generasi berpikir kritis. Mahasiswa yang hadir secara fisik tetapi absen secara intelektual akan menjadi calon pemimpin yang tidak siap menghadapi kompleksitas masa depan. Padahal pada tahun 2045, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, generasi Z akan berusia antara 33 hingga 48 tahun, masa produktif paling penting dalam siklus kehidupan manusia. Mereka akan menjadi ilmuwan, pendidik, pejabat, pengusaha, dan pembuat kebijakan. Namun jika sejak dini mereka gagal memahami prioritas, bekerja tidak efektif, dan tidak mampu mengelola diri sendiri, maka “Indonesia Emas 2045” hanya akan menjadi slogan tanpa isi.
Kekhawatiran ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan data BPS (2024) yang menunjukkan bahwa sekitar 20,31% generasi muda Indonesia (usia 15–24 tahun) tergolong NEET (Not in Employment, Education, or Training), atau setara dengan sekitar 9 juta jiwa muda yang tidak bekerja, tidak berkuliah, dan tidak mengikuti pelatihan produktif. Angka ini menunjukkan potensi kehilangan produktivitas generasi muda dalam jumlah besar jika tidak segera diatasi melalui pendidikan yang membangun kesadaran diri, tanggung jawab, dan manajemen waktu.
Dalam konteks ini, peran dosen menjadi sangat penting. Dosen bukan hanya pengajar materi kuliah, tetapi juga arsitek ekosistem intelektual. Dosen perlu hadir sebagai teladan berpikir dan berintegritas, memperlihatkan kedalaman analisis, konsistensi riset, dan kejujuran akademik. Ketika dosen berpikir kritis dan beretika, mahasiswa akan terdorong untuk meniru. Dosen harus mengubah ruang kuliah menjadi forum interaktif, bukan monolog satu arah; menciptakan tugas berbasis penelitian nyata; serta memberi umpan balik yang menantang agar mahasiswa tidak hanya tampil, tetapi juga tumbuh.
Selain itu, dosen perlu menumbuhkan mindfulness akademik, kesadaran untuk hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Banyak mahasiswa secara fisik hadir di kelas tetapi pikirannya mengembara ke media sosial. Melalui mentoring personal, refleksi kelompok, atau pelatihan manajemen diri, dosen dapat membantu mahasiswa belajar memusatkan perhatian dan mengenali potensi diri. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan nilai, tetapi menanamkan kebiasaan berpikir mendalam, fokus, dan reflektif. Dosen juga berperan menjaga wibawa forum ilmiah, dengan menegakkan penggunaan bahasa akademik yang santun, logis, dan kritis.
Lebih jauh lagi, kolaborasi lintas dosen, pusat karier, dan lembaga kemahasiswaan sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem pembelajaran yang holistik. Mahasiswa Gen Z membutuhkan lingkungan yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab berpikir. Kampus harus menjadi tempat yang membentuk karakter, bukan sekadar tempat beraktivitas.
Fenomena mahasiswa Gen Z yang gemerlap secara tampilan tetapi rapuh secara substansi bukan sekadar kritik terhadap mahasiswa; ini juga panggilan bagi para pendidik untuk berbenah. Pendidikan tinggi tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, melainkan harus menjadi ruang pembentukan manusia berpikir. Indonesia tidak membutuhkan generasi yang hanya “hadir secara fisik,” melainkan generasi yang hidup secara intelektual, sadar secara sosial, dan jujur secara moral. Jika dosen mampu memainkan peran strategisnya, sebagai mentor, fasilitator, dan teladan, maka dari balik gemerlap kosmetik kampus hari ini, akan lahir generasi yang benar-benar bersinar dengan cahaya pemikiran. (*/muz)