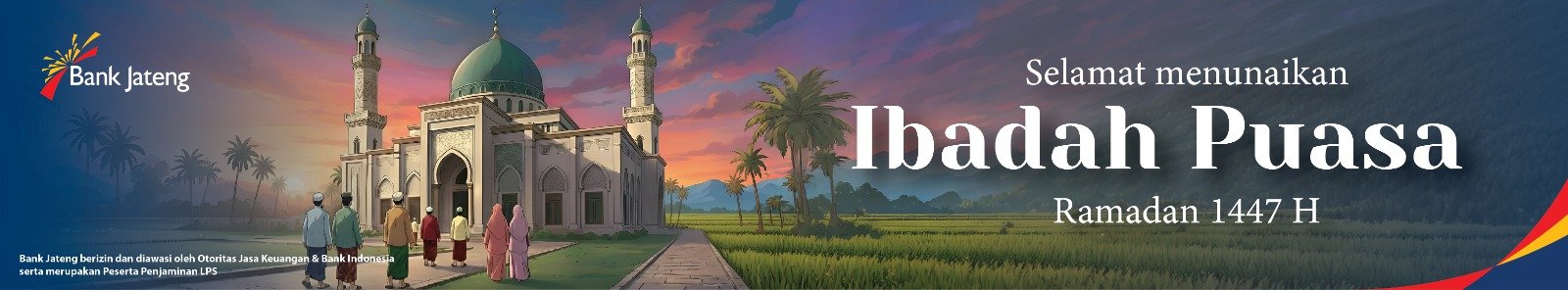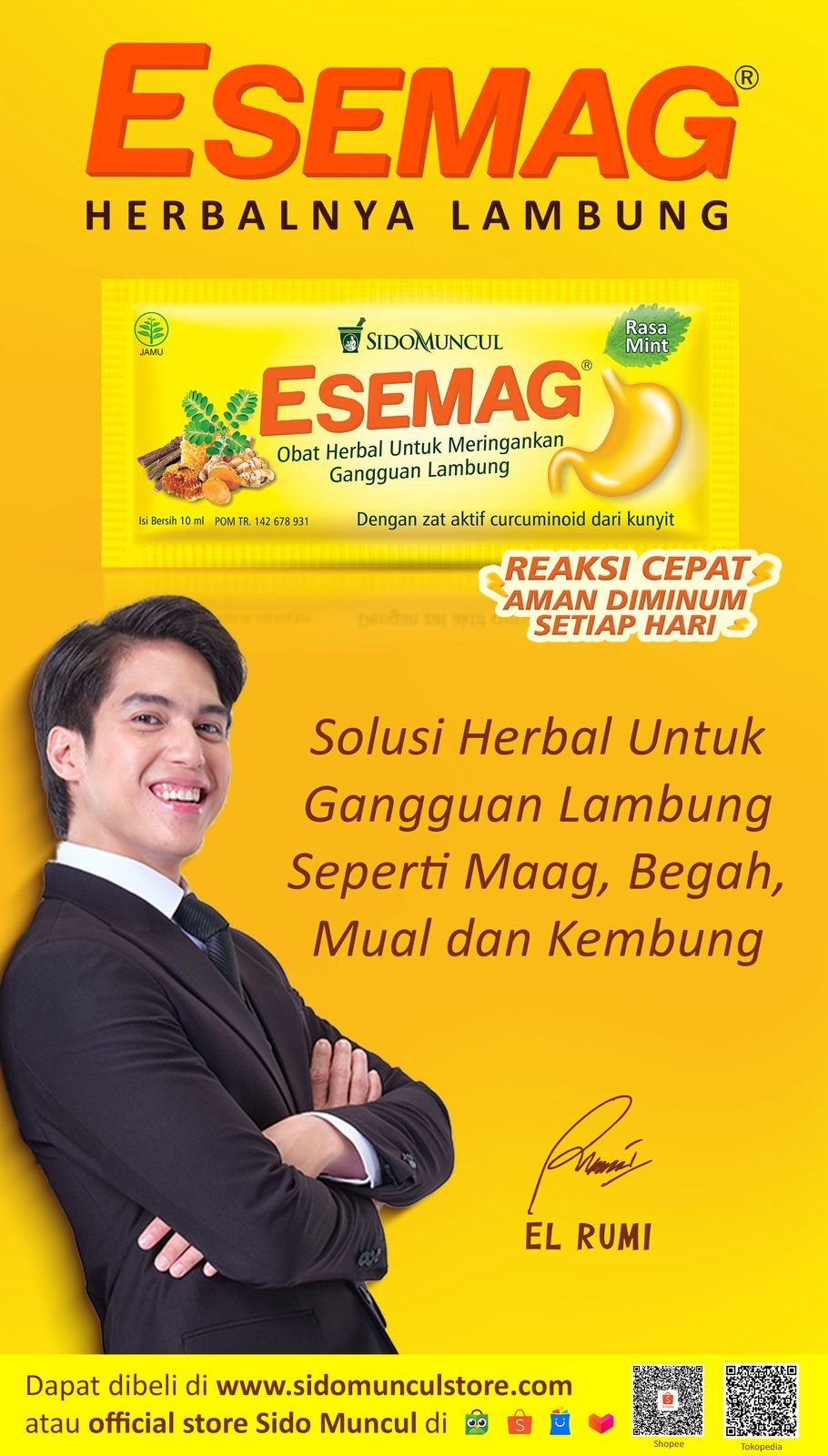Oleh: Mercy Bientri Yunindanova, S.P., M.Si., Ph.D. (Dosen Fakultas Pertanian UNS Surakarta)
DALAM beberapa tahun terakhir, AI (Artificial Intelligence), Kecerdasan Buatan, semakin banyak mendapat sorotan. Namun, sebenarnya AI bukanlah hal baru. Jejaknya sudah ada sejak perkembangan komputer setelah Perang Dunia II, dan Konferensi Dartmouth pada tahun 1956 sering dianggap sebagai awal lahirnya AI sebagai bidang ilmu tersendiri (Simpson, 2024).
Arsitektur Transformer menjadi dasar penting dalam perkembangan AI modern Sejak 2017. Teknologi ini membuat komputer lebih cepat dan pintar memahami bahasa, sehingga melahirkan model seperti BERT, GPT, dan akhirnya ChatGPT. Keberhasilan Transformer memicu pesatnya perkembangan dan investasi besar di bidang AI sejak awal 2020-an (Breitenbach, 2025).
Dalam forum Special Meeting on Global Collaboration, Growth and Energy for Development tahun 2024, Tanya Milberg, Manager Education 4.0 di World Economic Forum, menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi besar mendukung dunia pendidikan. Teknologi ini mampu mengambil alih berbagai pekerjaan administratif, sehingga guru dapat lebih fokus pada proses belajar-mengajar dan interaksi personal dengan murid.
Meski demikian, disampaikan juga bahwa siswa juga perlu dibekali pengetahuan tentang AI itu sendiri, mulai dari cara mengembangkannya hingga kesadaran akan risiko yang mungkin muncul.
Jika pada tingkat global AI dipandang sebagai peluang besar bagi pendidikan, maka tantangan di Indonesia justru terletak pada kedewasaan siswa dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi ini secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam sudut pandang saat ini, masalah utama pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia yang berkaitan dengan AI bukanlah soal “boleh atau tidak memakai AI”, melainkan kegagalan kolektif kita membangun literasi dan kerangka berpikir yang kokoh.
Sering kali ujian terlihat bagus, tugas tampak rapi, tetapi ketika ditanya mahasiswa ternyata tidak benar-benar memahami. Saat menyusun proposal pun, tulisan tampak rapi namun isinya tidak dipahami. Bahkan ketika diberi pertanyaan langsung, jawaban instan bisa muncul dengan meyakinkan, namun setelah ditelusuri ternyata hanya hasil bantuan AI tanpa pemahaman konsep yang mendalam.
Fenomena ini kerap berulang: tugas yang tampak rapi sesungguhnya rapuh, diksi terdengar meyakinkan tetapi argumen keropos, daftar pustaka panjang namun tanpa benang merah. AI memang mampu memperindah kalimat, tetapi kalimat yang bagus tidak otomatis melahirkan pikiran yang terstruktur.
Ketika fondasi bacaan pokok tidak dimiliki, ketika mahasiswa tidak punya rujukan teori yang jelas atau mazhab keilmuan yang dipilih secara sadar, AI justru menjadi mesin pengganda kebingungan, mempercepat yang sudah ada, dan yang ada sering kali adalah ketidakjelasan.
Kita perlu jujur mengakui bahwa literasi dasar, membaca kritis, menyaring argumen, memberi alasan dengan bukti, masih rendah pada banyak pelajar dan mahasiswa kita. Banyak yang terbiasa mengutip kalimat, bukan gagasan; menyalin skema, bukan memeriksa asumsi di balik skema. Ketika AI hadir, kebiasaan ini seperti mendapat “turbo”: draf cepat jadi, bahasa mulus, kutipan tampak resmi.
Namun di balik permukaan rapi, sering tak ada posisi ilmiah: teori apa yang dipakai, mengapa tepat untuk kasus ini, apa alternatifnya, dan apa keterbatasannya. Di sinilah letak bahayanya, AI menciptakan ilusi kompetensi: tampak bisa, padahal tidak. Ilusi kompetensi merupakan gejala psikologis ketika individu menilai kemampuan dan pengetahuan dirinya lebih tinggi daripada yang sebenarnya dimiliki (Kruger & Dunning, 1999).
Bahaya kedua adalah hilangnya kepekaan konteks. AI dilatih dari data global dan sering tidak peka pada kondisi lokal, sehingga jawabannya cenderung menyamaratakan. Mahasiswa yang kerangka berpikirnya belum kuat bisa mudah terbawa, lalu menganggap jawaban umum sebagai kebenaran mutlak.
Padahal ilmu selalu lahir dari konteks: ekologi, budaya, dan data lapangan. Tanpa kebiasaan memeriksa apakah jawaban sesuai dengan data kita atau apakah asumsi yang dipakai benar, AI bisa menyeret kita pada ‘copy-paste pengetahuan’: gagasan dari luar langsung ditempel ke realitas lokal tanpa penyesuaian.
Masalah ketiga adalah ketiadaan landasan keilmuan. Dalam banyak bidang ada tradisi positivistik (Park, Konge, & Artino, 2020), yang menekankan pengetahuan objektif dan terukur, serta tradisi konstruktivistik (Belharar, Laamrani, & Chakor, 2023), yang melihat pengetahuan dibangun dari pengalaman dan konteks sosial.
Mahasiswa perlu punya pijakan yang jelas karena setiap pilihan tradisi berarti juga memilih cara bertanya, cara membuktikan, dan standar kebenaran tertentu. Sayangnya, banyak mahasiswa sekarang tidak lagi terbiasa mencari sumber yang terpercaya; mereka cenderung ingin yang instan dan enggan menghadapi proses berpikir yang sulit. Tanpa pijakan dan kebiasaan akademik yang kuat, mahasiswa hanya akan menjadikan AI seperti mesin fotokopi, mampu menyalin apa saja, tetapi tanpa benar-benar memahami isinya.
Karena itu, peran pendidik, guru, dosen, hari ini bukan menutup pintu bagi AI, melainkan menjadi jangkar nalar bagi siswa dan mahasiswa. Artinya, pendidik perlu memberi arah bacaan yang jelas, misalnya buku atau tulisan utama yang wajib dipahami, lalu membandingkannya dengan sumber lain agar terlihat perbedaan cara pandang. Pendidik juga perlu menuntut proses yang nyata, mulai dari catatan asumsi, alasan memilih metode, sampai jejak revisi dari draf ke draf.
Selain itu, pendidik harus menjaga integritas dengan meminta keterbukaan penggunaan AI, menguji pemahaman lewat tanya jawab, serta menolak karya yang hanya indah secara bahasa tetapi kosong isinya. Siswa dan mahasiswa boleh menggunakan AI sebagai alat bantu, misalnya untuk memantik ide, merapikan bahasa, merangkum bacaan, atau membuat draf awal dengan syarat jelas menyebutkan penggunaannya, memeriksa ulang kebenaran isi, dan bertanggung jawab penuh atas kesimpulan akhirnya.
Mahasiswa perlu dibiasakan dengan literasi yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar ringkasan. AI boleh membantu mencari rujukan atau merapikan bahasa, tetapi keputusan untuk menerima atau menolak suatu argumen harus lahir dari proses berpikir mereka sendiri. Tanpa literasi seperti ini, kuliah hanya menjadi pameran kata-kata indah tanpa isi.
Untuk itu, siswa dan mahasiswa perlu dilatih agar dewasa dalam mengenal AI, bukan sekadar memakainya secara instan, tetapi memahami cara kerja, batasan, dan risikonya. Peraturan mungkin sudah ada, tetapi peran guru dan dosen jauh lebih penting sebagai pendamping langsung: memberi peta berupa kerangka konseptual, kompas berupa metode dan standar bukti, serta rambu berupa etika penggunaan AI. Dengan pendidik sebagai jangkar, AI tidak lagi menjerumuskan, tetapi justru mendampingi siswa dan mahasiswa Indonesia tumbuh dewasa, kritis, dan bertanggung jawab dalam belajar maupun berkarya. (*)